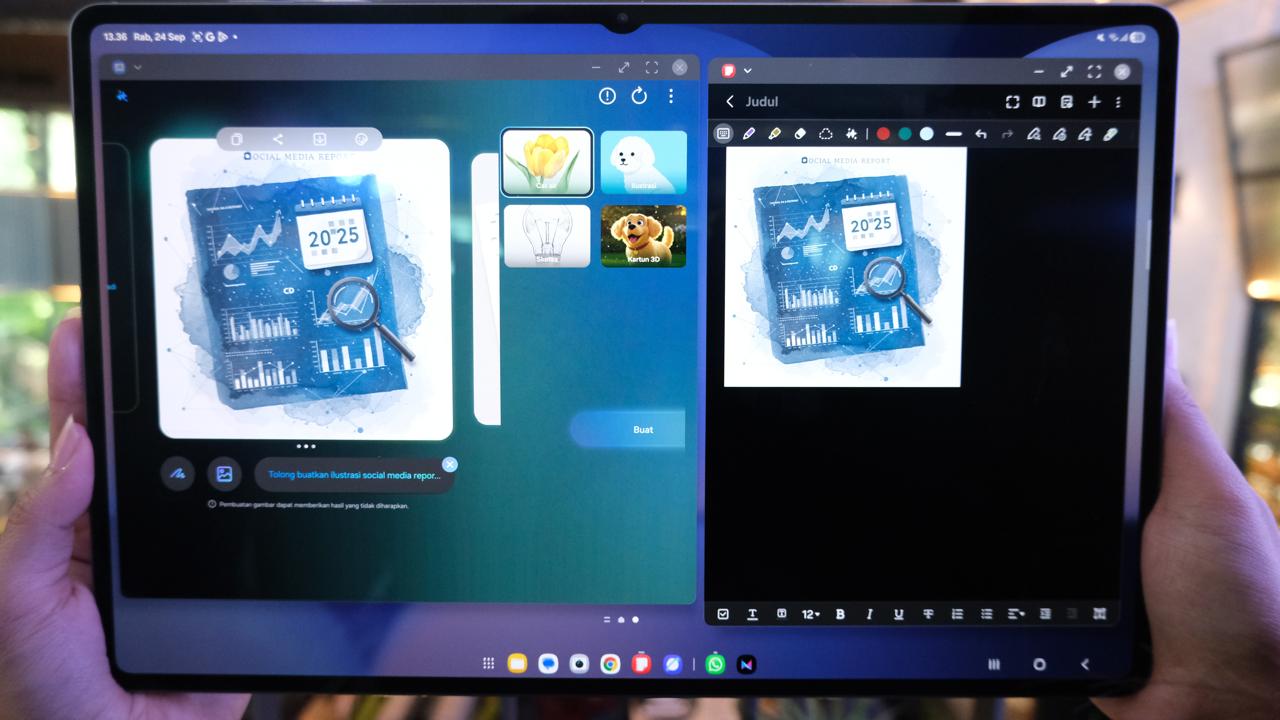Solotrust.com - Di antara bendera yang berkibar dan pekik merdeka yang menggema setiap 17 Agustus, terselip satu kenyataan yang tak bisa kita abaikan: kita belum sepenuhnya merdeka dari sampah, dari kelalaian, dari kebiasaan membuang sampah tanpa berpikir panjang.
Setiap lembar plastik yang terombang-ambing di selokan, setiap kaleng minuman yang teronggok di tepi jalan, adalah saksi bisu peradaban yang belum berdamai dengan sisa dirinya sendiri. Dalam sunyi tempat pembuangan akhir, merdeka kehilangan maknanya.
Maka kita pun bertanya: apa arti kemerdekaan, jika tanah yang kita cintai perlahan dicekik oleh sampah yang kita hasilkan sendiri? Kita telah 80 tahun merdeka dari kolonialisme, tapi belum benar-benar merdeka dari gaya hidup yang mencederai bumi. ada satu ruang sunyi yang jarang disorot: tumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan, mengendap dalam saluran air, menyumbat di hulu sungai.
Sejatinya, negara telah memberi pedoman lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini bukan sekadar dokumen birokrasi, melainkan sebuah peta jalan untuk berpindah dari era "kumpul-angkut-buang" menuju peradaban pemilah, pemanfaat, dan pelestari. Di dalamnya tertulis jelas: pengelolaan sampah adalah tanggung jawab Bersama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Ia bukan sekadar tumpukan pasal, tetapi manifesto ekologis: bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan petugas kebersihan. Bahwa daerah diberi amanat bukan untuk sekadar mengangkut, tapi mengelola.Bahwaprodusen wajib bertanggung jawab atas limbah produknya.
Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah yang berjalan tanpa peta, tanpa dana yang cukup, tanpa kemauan politik yang kuat. Banyak regulasi hanya mengendap di laci, tak pernah hidup di jalan-jalan dan pasar-pasar.
Sementara itu, suara moral datang dari langit melalui Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 yang mengharamkan membuang sampah sembarangan, dan mewajibkan pengelolaan sampah sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Fatwa ini menegaskan bahwa mencemari bumi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Tuhan.
Dalam bahasa yang lebih halus tapi tajam, fatwa ini menyatakan bahwa membuang sampah sembarangan adalah perbuatan haram, dan bahwa mengelola sampah adalah bagian dari ibadah. Fatwa ini membumikan ajaran agama ke dalam problem ekologis kontemporer. Ia bukan hanya peringatan, tapi panggilan: bahwa membersihkan bumi adalah bagian dari membersihkan hati.
Namun suara langit pun kerap kalah oleh kebisingan pusat perbelanjaan dan riuh konsumsi digital. Hanya segelintir pesantren, masjid, dan komunitas umat yang benar-benar mengamalkan nilai itu sebagai gerakan. Dua instrument hukum dan hati Nurani sebenarnya telah terbit. Tapi pertanyaannya: mengapa kita masih kalah oleh sampah?
Di balik tumpukan kertas dan plastik, tersembunyi ironi. Regulasi ada, tapi pengawasan lemah. Fatwa ada, tapi belum membumi. Pemerintah daerah banyak yang terseok karena keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Banyak kota besar masih bergantung pada TPA yang makin hari makin sesak.Di sisi lain, masyarakat belum terbiasa memilah, belum tergerak untuk mengurangi. Sampah masih dianggap urusan petugas kebersihan. Dan swasta ? Hanya segelintir yang sungguh-sungguh memikul tanggung jawab produsennya.
Di satu sisi, hukum negara telah bicara, tapi pelaksanaannya setengah hati. Di sisi lain, agama telah memberi peringatan, tapi umat terlalu sibuk dengan urusan dunia. Sampah pun terus menumpuk tak hanya di TPA, tapi juga di hati yang terbiasa membuang, di sistem yang tak pernah tuntas, di budaya yang tak merasa bersalah.
Sungai menjadi museum limbah. Laut menjadi kuburan plastik. Udara mengangkut debu sisa pembakaran.Kita hidup di tengah paradoks: mengeluh saat banjir, tapi menutup mata ketika membuang plastik ke selokan. Ingin udara bersih, tapi enggan memilah sampah. Ingin Indonesia hijau, tapi menolak berubah. Dan bumi pun berteriak dalam diam melalui banjir, pencemaran udara, bau tak sedap, dan anak-anak yang tumbuh di pinggiran TPA.
Kita belum terlambat. Merdeka dalam sampah bukan utopia, tapi kerja bersama. Di kampung-kampung yang membentuk bank sampah, di sekolah-sekolah yang mengajarkan pilah dari kecil, di masjid-masjid yang menggalang sedekah sampah untuk dana sosial, di perusahaan-perusahaan yang mulai menerapkan Extended Producer Responsibility. Inilah saatnya tiga pilar bersatu: masyarakat, pemerintah daerah, dan swasta.
- Pemerintah daerah wajib menyusun peraturan turunan UU 18/2008 secara spesifik, berpihak pada edukasi, insentif, dan teknologi hijau.
- Masyarakat harus didorong dari partisipatif menjadi transformatif: sadar bahwa setiap sampah yang dibuang sembarangan adalah bentuk pengkhianatan terhadap tanah air.
- Swasta perlu keluar dari peran pasif. Jadikan tanggung jawab lingkungan sebagai inti bisnis, bukan hanya CSR simbolik.
Dan yang paling penting: mari kita hidupi kembali fatwa. Biarkan ia turun dari mimbar ke halaman rumah. Biarkan ia tak sekadar dibaca, tapi dijalani. Merdeka dalam sampah artinya bebas dari keacuhan. Merdeka dalam sampah artinya berani menata ulang cara kita hidup, konsumsi, dan memperlakukan bumi.Karena tanah ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan dari cucu-cucu kita. Dan tak ada yang lebih menyakitkan dari mewariskan tanah air yang penuh luka. "Setiap sampah yang kita buang sembarangan adalah surat cinta yang salah alamat ditujukan pada bumi, tapi menyakitinya."
*) Oleh: Arif Sumantri. Penulis adalah Guru Besar Kesehatan Lingkungan UIN Jakarta/Ketua Umum PP HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia)
(and_)








.jpg)

.jpg)